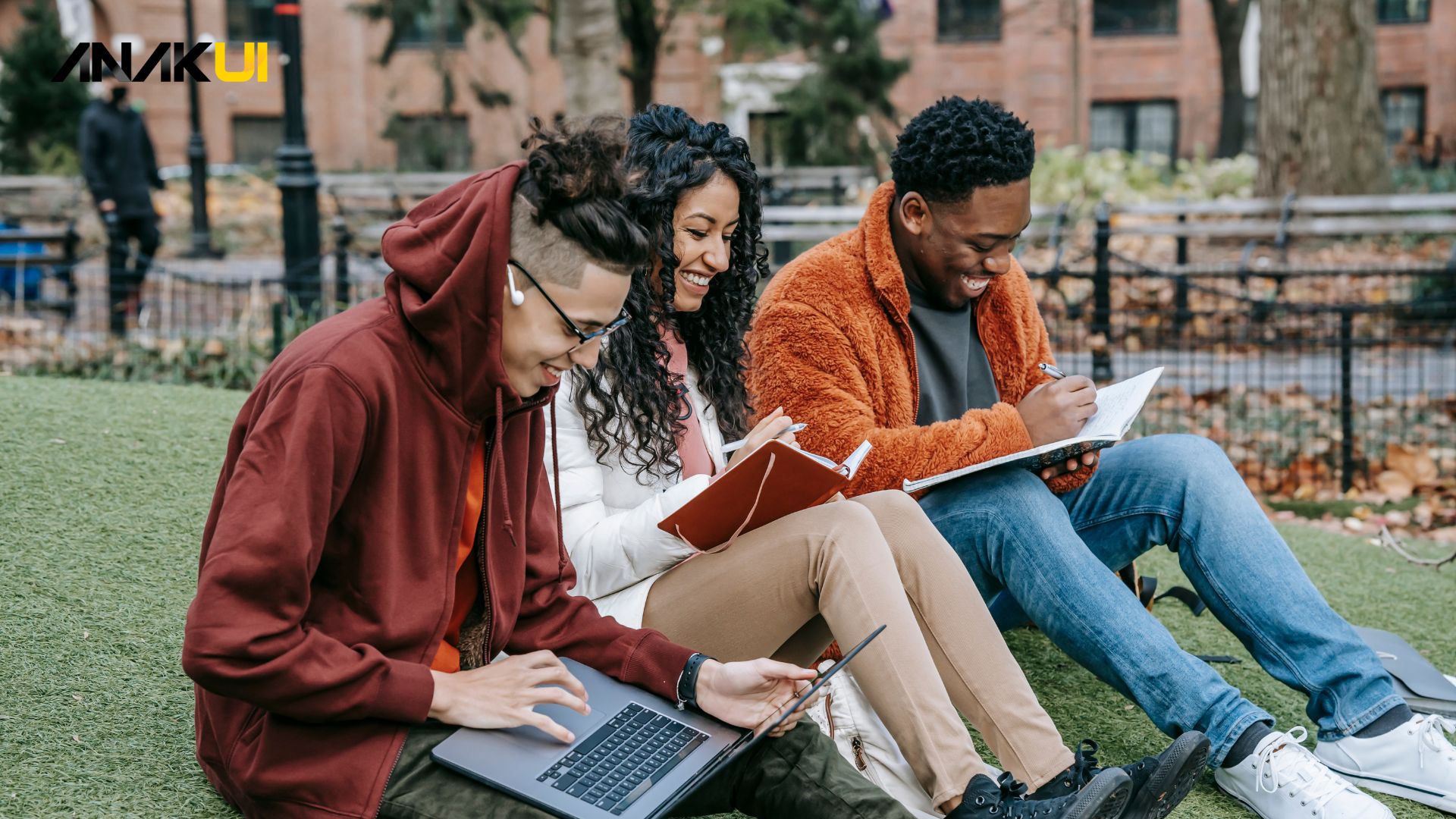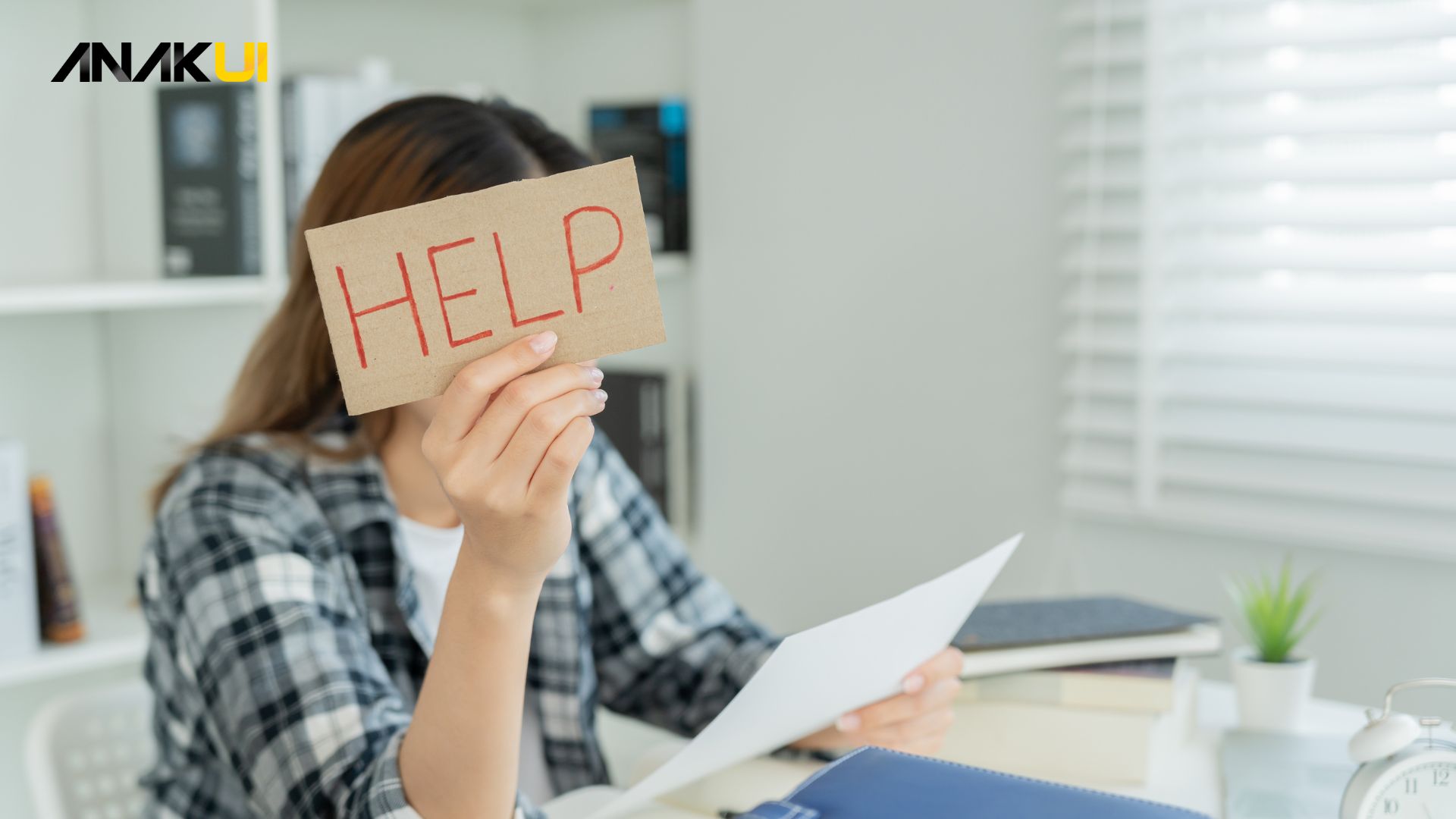Pentingnya Soft Skill Bagi Mahasiswa, Wajib Paham
Anakui.com – Pentingnya soft skill bagi mahasiswa ini perlu diperhatikan oleh setiap mahasiswa demi memperlancar karir di masa depan. Mahasiswa adalah jantung dan jiwa dari sebuah institusi pendidikan tinggi. Mereka bukan hanya berkutat pada aspek akademis, tetapi juga menjadi pembentuk karakter dan potensi individu yang akan memengaruhi masa depan mereka. Di zaman yang terus berubah … Read more