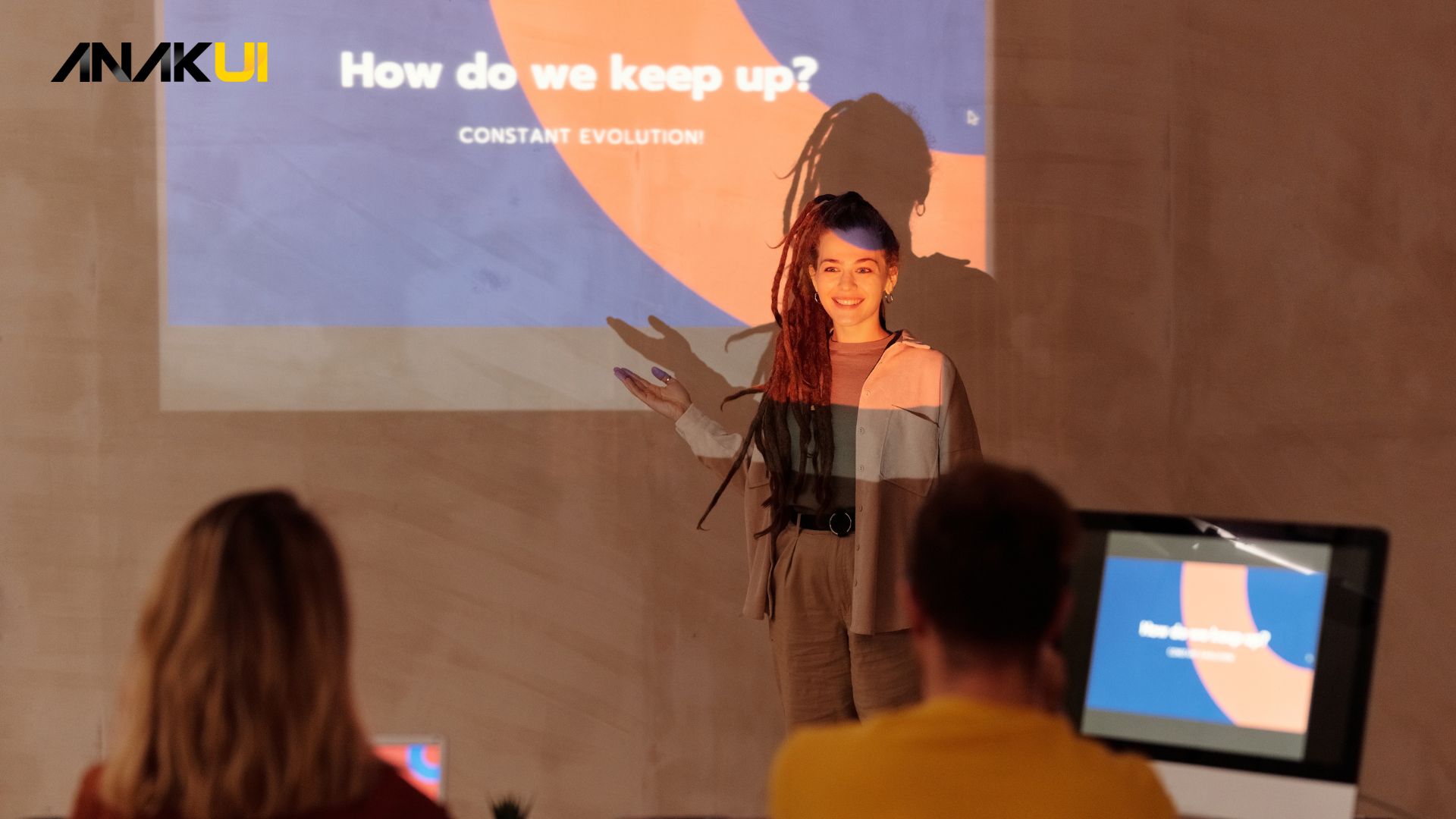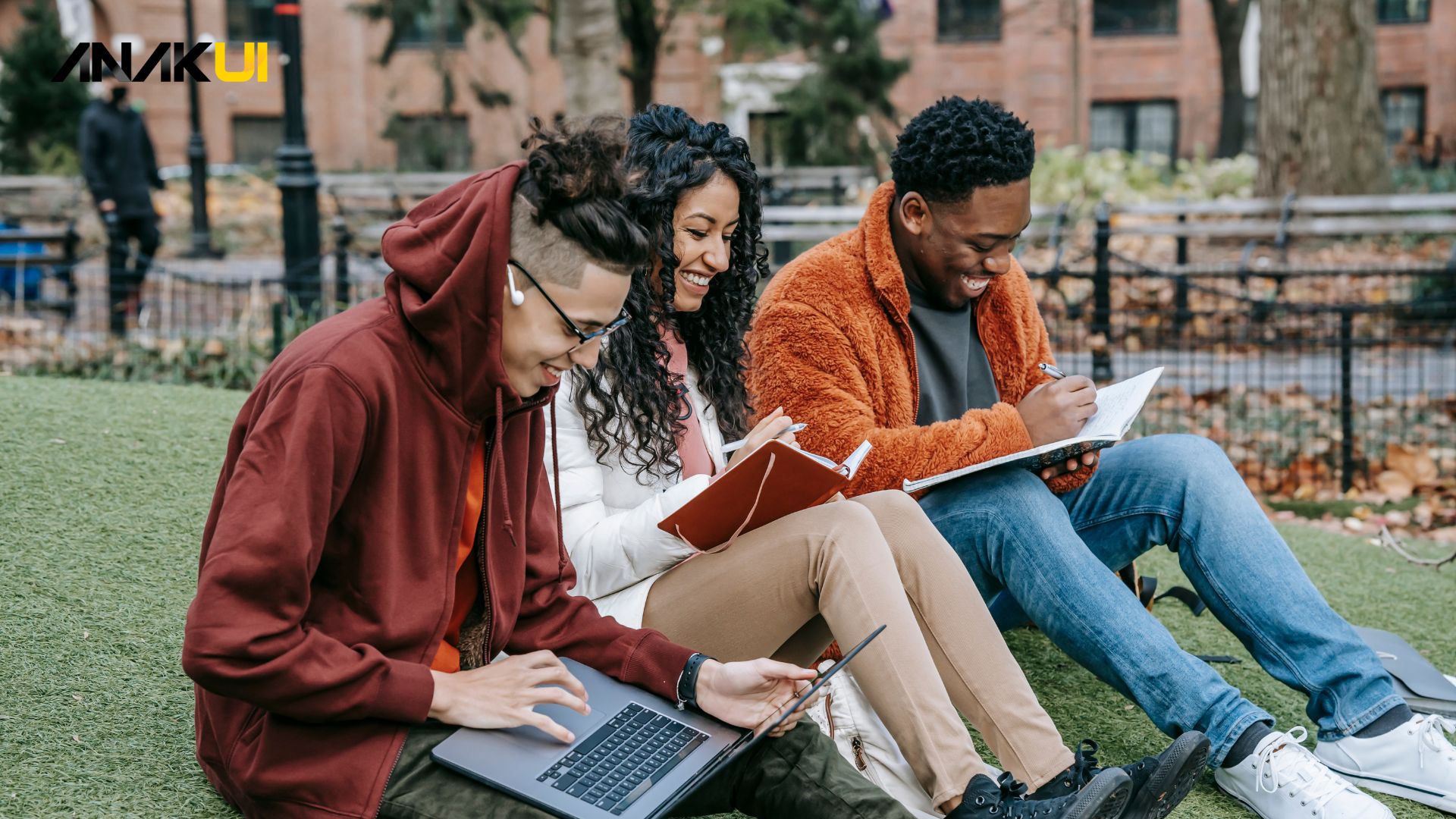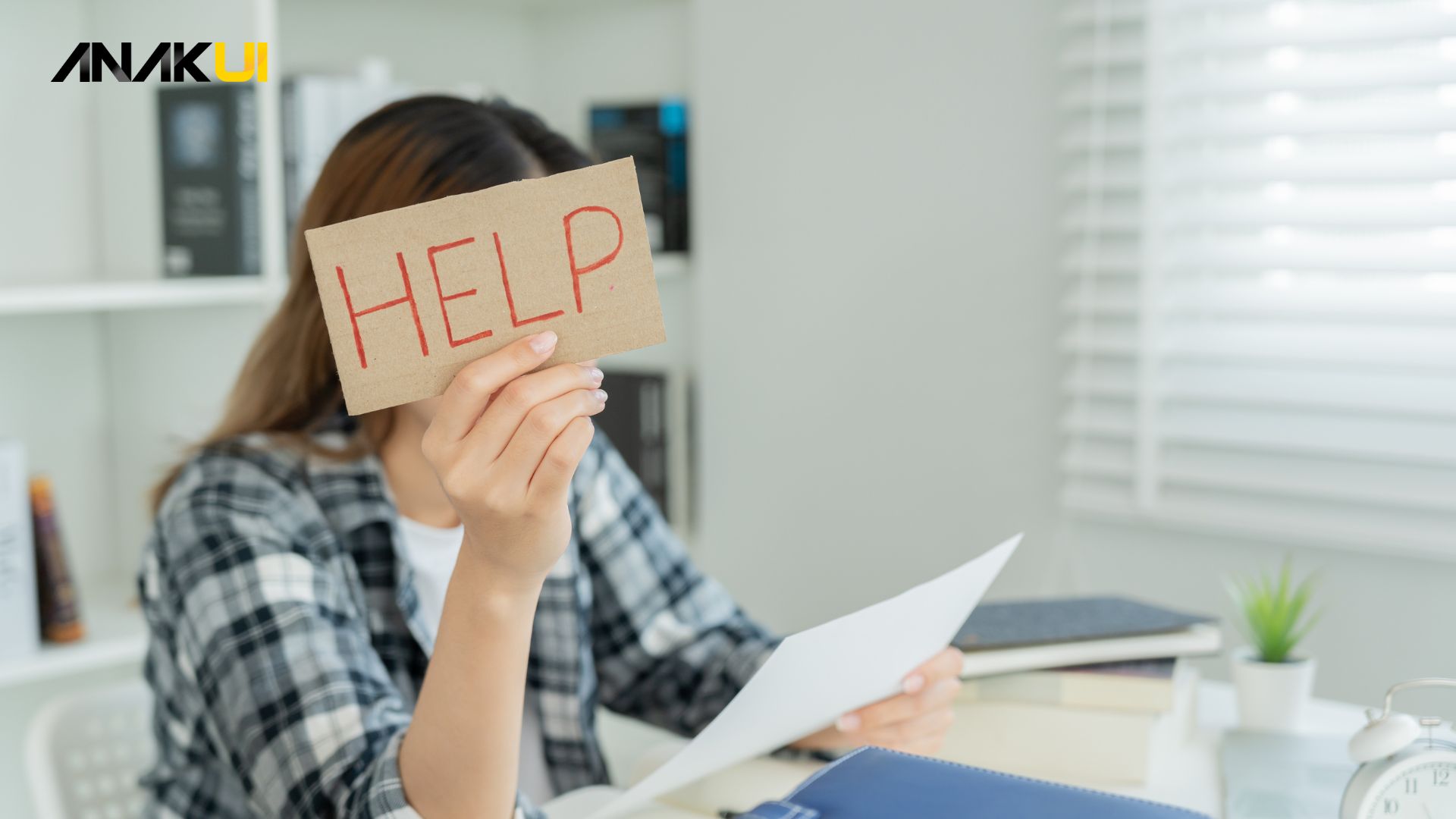Cara Membuat KIP Kuliah Terlengkap, Wajib Cermati
Anakui.com – Cara membuat KIP kuliah ini wajib dicermati oleh setiap calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam memajukan diri dan mencapai cita-cita. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa biaya pendidikan seringkali menjadi hambatan bagi banyak individu, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Cara … Read more